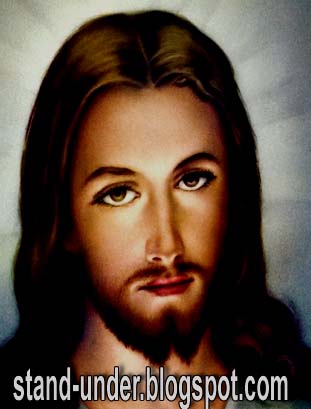PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengajak Nahdlatul Ulama (NU) untuk aktif mencegah hoaks dan fitnah yang kian merebak menjelang Pemilihan Umum 17 April mendatang. Menurut Jokowi, berita bohong sudah berada pada tingkat yang memprihatinkan. “Ada 9 juta rakyat Indonesia yang percaya pada berita bohong,” kata Jokowi ketika membuka acara Munas dan Konbes NU Tahun 2019 di Ponpes Miftahul Huda Al-Azhar, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu, 27 Februari 2019 (Bdk. MI, 27/02/2019).
Kecemasan Jokowi sesungguhnya bukan baru dalam sejarah politik. Usia kebohongan sama panjangnya dengan usia politik itu sendiri. Kebohongan dekat dengan politik karena politik berurusan dengan kekuasaan.
Politik dapat membuat keputusan tentang hidup dan matinya seseorang: menyangkut perang, hukuman mati, kebijakan kesehatan publik dan hak-hak sosial. Jadi politik berkuasa memutuskan siapa yang boleh hidup dan siapa yang tak boleh hidup. Kekuasaan negara yang omni potenc ini membuat politik selalu bersinggungan dengan soal abuse of power atau kebohongan.
Kekuasaan fake news kini bertambah dahsyat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi digital dan penggunaan media sosial. Di samping itu, fakta merosotnya kepercayaan publik terhadap media mainstream mendorong orang mencari sendiri informasi di media sosial yang menyambutnya dengan suguhan jutaan fake news.
Kebohongan dalam sejarah
Kebohongan politik bukan cerita baru. Ada tiga contoh klasik kebohongan dalam sejarah filsafat politik (Bdk. Barbara Zehnpfennig, 2017). Pertama, dalam masyarakat Yunani Kuno kepada masyarakat Ionia di Asia Kecil selalu diajarkan bahwa kota-kota di Asia Kecil itu didirikan oleh orang-orang Yunani.
Kebohongan itu diindoktrinasi secara terus-menerus dan disebarkan secara luas, sehingga akhirnya masyarakat Asia Kecil percaya. Narasi kebohongan itu menjadi basis legitimasi bagi masyarakat Yunani untuk menguasai Asia Kecil dan menagih pajak dari mereka untuk kepentingan penguasa Yunani.
Kedua, pada abad ke-17 tersebar berita di Kerajaan Inggris tentang konspirasi (popish plot) sejumlah imam Yesuit untuk membunuh Raja Inggris. Berita ini telah menimbulkan kemarahan massal rakyat Inggris dan krisis politik yang berakhir pada hukuman mati terhadap 35 imam Yesuit.
Akibatnya, Raja Charles II mengeluarkan undang-undang (Exclusion Bill) anti-Gereja Katolik di Inggris. Kemudian diketahui bahwa berita konspirasi itu hanya fake news yang diciptakan seorang mantan imam Anglikan bernama Titus Oates (Titus the Liar) yang benci dan menghendaki kehancuran Gereja Katolik di wilayah Kerajaan Inggris.
Ketiga, selama abad ke-20 sejumlah rezim totalitarian membangun kekuasaan di atas kebohongan. Bahkan konon mantan Presiden Rumania, Ceausescu melakukan manipulasi atas ramalan cuaca. Ia meyakinkan rakyat Rumania bahwa kedinginan pada musim dingin itu hanya ilusi. Jadi tidak perlu menuntut pemerintah untuk menyediakan gas dan alat pemanas di rumah-rumah warga. Di Indonesia rezim Orde Baru ialah rezim kebohongan yang membangun kekuasaan selama 32 tahun atas dasar manipulasi sejarah.
Etika politik dan hoaks
Ketiga kisah sejarah di atas menunjukkan peran kebohongan dalam mempertahankan atau meraih kekuasaan. Dewasa ini pun politik selalu berurusan dengan persoalan janji kampanye yang tak dapat dipenuhi, insenuasi politik, retorika hiperbolis, dan trik menyembunyikan kebenaran. Bagaimana etika politik menyikapi narasi kebohongan dalam dunia politik?
Filsuf politik dari Florens pada awal masa pencerahan, Niccolo Machiavelli (1469-1527) berpandangan bahwa kebohongan, manipulasi data, dan kemunafikan merupakan instrument legitim dalam pertarungan politik.
Sebab dalam dunia yang hanya dihuni manusia primitif tanpa peradaban dan moralitas, seorang yang taat hukum sudah pasti akan binasa. Karena semua manusia dari kodratnya jahat, tak ada imperati yang perlu ditaati. Kontrak dan janji dapat saja dilanggar tanpa harus takut pada sanksi.
Filsuf Jerman, Immanuel Kant (1724-1804) mengkritik keras legitimasi kebohongan Machiavelli. Bagi Kant tak ada toleransi atas kebohongan. Argumentasinya ialah, setiap pelanggaran atas aturan yang berlaku umum mengguncangkan dan mendelegitimasi aturan itu sendiri.
Dampak dari pelanggaran itu jauh lebih besar dari akibat buruk yang ditimbulkan sebuah kejujuran tanpa syarat atau kategoris.
Kant berpandangan bahwa seorang Yahudi yang dikejar tentara Nazionalsozialismus (Nazi) dan bersembunyi di dalam rumah orang lain, tuan rumah tersebut berkewajiban untuk memberitahukannya.
Sebab, kerugian yang disebabkan kejujuran itu masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan melanggar imperatif 'jangan berbohong'. Dengan kata lain, menurut Kant taat pada larangan untuk berbohong jauh lebih penting daripada keselamatan nyawa orang yang tak bersalah.
Epistemologi demokrasi
Apakah rigorisme Kantian ini merupakan sikap etis yang benar dalam berhadapan dengan perkara kebohongan? Pertanyaan ini sudah menyibukkan Plato pada era Yunani Kuno. Agar politik tidak dibangun di atas pilar dusta, Plato menganjurkan model filsuf (pencinta kebijaksanaan dan kebenaran) sebagai raja.
Filsuf raja tidak saja taat pada kebenaran, tapi juga tunduk pada prinsip kesejahteraan umum. Bahkan dalam kondisi tertentu, demi kesejahteraan umum, kebohongan dipandang legitim.
Tak seperti Machiavelli, Plato mewajibkan filsuf raja untuk taat pada prinsip-prinsip etis. Melampaui Kant, filsuf raja tak pernah boleh memandang prinsip etis sebagai sebuah substansi esensialistik ahistoris, tapi ruang prosedural yang harus diberi substansi baru dalam terang tanda-tanda zaman.
Untuk itu seorang pemimpin perlu dibekali dengan “daya penilaian” (Urteilskraft) yang menurut Plato hanya dapat dipelajari dalam studi filsafat yang sangat panjang. Dengan demikian sang pemimpin akhirnya paham bahwa kesejahteraan yang dikejarnya bukan kesejahteraan para penguasa dan keluarganya seperti yang kita saksikan dalam praktik politik di Tanah Air, tapi kesejahteraan rakyat banyak terutama mereka yang paling miskin.
Plato menganjurkan agar demokrasi tidak dibangun di atas pilar kebohongan Machiavellian, tapi di atas landasan epistemologis. Bukan epistemologi rigoristis Kantian yang mengorbankan keselamatan manusia yang tak bersalah. Tapi, epistemologi yang dapat menyembunyikan kebenaran jika mendatangkan kebaikan lebih besar bagi yang paling tak beruntung. Jika tidak demikian, kebohongan itu harus dihukum seberat-beratnya.
Penulis: Otto Gusti Dosen Filsafat dan HAM di STFK Ledalero, Maumere, Flores, NTT, Doktor Hochschule für Philosphie, München, Jerman. http://mediaindonesia.com/read/detail/220839-epistemologi-demokrasi